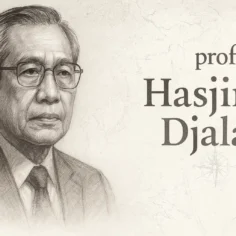Bataha Santiago dikenang sebagai Raja Sangihe Penantang VOC yang memilih bertahan pada kedaulatan lokal ketimbang tunduk pada monopoli rempah. Jejaknya paling kuat terbaca di Manganitu, Sangihe, wilayah perbatasan laut yang sejak lama menjadi simpul pertemuan jalur dagang Nusantara–Pasifik. Di tengah arus besar kekuasaan dan misi dagang kolonial, ia berdiri pada pilihan yang mahal: mempertahankan martabat komunitas pesisir meski berisiko kehilangan nyawa.
Lansekap Sangihe: Gerbang Utara Nusantara
Posisi Sangihe unik—lebih dekat ke Filipina dibandingkan ke pusat kekuasaan di Jawa. Perairannya menjadi jalur alami perahu dagang, kapal misi, dan armada kekuatan asing. Sejak abad ke-17, cengkih dan hasil bumi pesisir adalah “emas” yang diperebutkan. Lintasan niaga ini membentuk masyarakat Sangihe yang terbiasa berinteraksi lintas budaya, sekaligus rentan terhadap upaya pemusatan kontrol perdagangan oleh kekuatan luar.
Pada fase inilah muncul nama Bataha Santiago. Dalam ingatan setempat, ia disebut dengan beberapa varian ejaan (mis. Don Jogolov/Jugov Sint Santiago). Variasi ejaan bukan persoalan; yang penting ialah perannya sebagai pemimpin yang memahami bahwa kontrak dagang bukan sekadar soal harga dan panen, tetapi menyentuh ranah kedaulatan, keyakinan, dan tatanan sosial.
VOC dan Kontrak Panjang: Monopoli yang Mengikat
Untuk mengunci pasokan dan harga, VOC memperkenalkan kontrak dagang-politik yang memusatkan kontrol tanaman dan distribusi rempah. Bagi kerajaan pesisir seperti Manganitu, kontrak itu terasa menekan: pembatasan menanam, kewajiban menjual melalui kanal resmi, serta sanksi berat untuk pelanggaran. Secara ekonomi, komunitas kehilangan keleluasaan; secara politik, otoritas raja tereduksi; secara budaya, datang tekanan nilai dari luar.
Di titik inilah Raja Sangihe Penantang VOC tampil. Bataha Santiago menilai kontrak semacam itu timpang, tak memberi ruang adil bagi masyarakat yang selama ini hidup dari laut dan kebun. Ia membaca bahwa menerima kontrak berarti menyerahkan kontrol atas nasib sendiri—dan itu tidak bisa dinegosiasikan.
Diplomasi yang Macet, Meriam yang Bicara
Upaya persuasif lazim mendahului kekerasan. Tetapi ketika negosiasi tak berbuah, armada bersenjata menjadi bahasa berikutnya. Narasi lokal mencatat beberapa kali upaya pemaksaan, dari ancaman sampai penyerbuan. Pertahanan Manganitu bertumpu pada jaringan solidaritas kampung pesisir—perahu ringan, medan yang dikenali, dan keberanian yang dirawat oleh tradisi pelaut. Namun daya tembak dan logistik musuh sukar ditandingi dalam perang panjang.
Pada akhirnya, Bataha Santiago ditangkap. Banyak versi lisan menyebut eksekusi dilakukan di Tahuna. Kalimat yang sering dikutip untuk merangkum sikapnya: lebih baik tiang gantungan daripada tunduk pada kesewenang-wenangan. Apakah kalimat itu persis demikian atau telah disarikan dari banyak tutur, esensinya sama: ia memilih menanggung konsekuensi paling berat demi memelihara marwah komunitas.
Gelombang yang Tak Padam: Ingatan dan Toponimi
Walau hayatnya terputus, Raja Sangihe Penantang VOC tidak padam. Ingatannya hidup di toponimi, monumen, dan cerita yang diturunkan. Nama tempat—teluk, tanjung, lapangan—sering menyematkan “Santiago” sebagai penanda. Patung dan tugu menjadi penyangga memori; bukan sekadar dekorasi, melainkan pernyataan bahwa wilayah perbatasan pernah berdiri menegakkan haknya.
Di rumah sendiri, ingatan kolektif ini berfungsi sebagai jangkar identitas. Anak-anak pesisir belajar bahwa laut bukan hanya sumber nafkah, melainkan ruang martabat yang harus dibela. Kisah Bataha Santiago membantu menanamkan pelajaran penting: kekuasaan boleh datang dari jauh, tetapi keputusan akhir tentang siapa kita berada di tangan sendiri.
Relevansi Kontemporer: Dari Cengkih ke Keadilan Ekonomi
Apa pelajaran praktis dari sejarah ini? Pertama, asimetri kekuasaan dalam perdagangan—dulu dalam bentuk kongsi dagang bersenjata, hari ini bisa berupa struktur pasar, kontrak produksi, atau ketergantungan logistik—selalu menuntut kewaspadaan. Kedua, kedaulatan ekonomi lokal perlu dijaga melalui tata kelola yang memberi ruang pada produsen kecil, akses informasi harga, dan saluran distribusi yang adil. Ketiga, narasi dari perbatasan harus hadir di panggung nasional; jangan sampai sejarah dimonopoli oleh poros-poros besar saja.
Menelisik Bataha Santiago bukanlah romantisme masa lalu. Ia cara untuk memahami bahwa praktik monopoli dan kontrak timpang punya konsekuensi sosial yang nyata: migrasi paksa tenaga kerja, pengkerdilan otoritas adat, hingga hilangnya diversifikasi ekonomi pesisir. Dengan menyimak kisah Manganitu, kita menyusun peta etika dagang yang relevan untuk diskusi hari ini—mulai dari tata niaga hasil laut, pengelolaan pangan lokal, sampai kebijakan investasi yang berpihak.
Baca Juga:
5 Tokoh Bahari Nusantara yang Terlupakan
Jejak Benda dan Cerita: Menghidupkan Ruang Pamer
Bagaimana memvisualkan jejak Raja Sangihe Penantang VOC di ruang pamer atau ruang digital?
- Panel rempah: Cengkih sebagai aktor utama; jelaskan siklus tanam, harga, dan kenapa ia diperebutkan.
- Senjata & perisai pesisir: Benda bukan hanya alat perang; ia merekam estetika dan teknologi lokal.
- Peta rute niaga: Tunjukkan hubungan Sangihe–Maluku–Filipina untuk memahamkan konteks geopolitik.
- Kronik singkat kontrak monopoli: Bukan untuk menggurui, melainkan memberi kerangka agar pembaca bisa menilai sendiri.
Pendekatan ini membuat pengunjung bukan sekadar “melihat benda”, tetapi mendengar suara orang-orang yang hidup di sekelilingnya—para penanam, tukang perahu, pedagang, dan keluarga yang menanti di pesisir.
Garis Waktu Ringkas
- Awal–pertengahan abad ke-17: Sangihe menguat sebagai simpul dagang; cengkih menjadi komoditas kunci.
- Masa kepemimpinan Bataha Santiago: Penolakan terhadap kontrak monopoli memicu ketegangan berkepanjangan.
- Puncak konflik: Upaya pemaksaan berujung penyerbuan; Manganitu bertahan sejauh mungkin dengan sumber daya lokal.
- Eksekusi di Tahuna: Riwayat hidup berakhir, namun memori sosial dimulai—menjelma toponimi, monumen, dan semboyan.
- Era kini: Penguatan narasi kepahlawanan perbatasan; kisah Sangihe ditempatkan dalam mosaik sejarah maritim Nusantara.

Penutup
Kisah Bataha Santiago memperlihatkan keberanian memilih jalan sulit demi harkat komunitas. Ia bukan sekadar catatan perlawanan; ia cermin yang memantulkan pertanyaan ke masa kini: apa arti merdeka jika urusan nafkah dan harga ditentukan pihak yang tak hadir di kampung kita? Dengan menghidupkan ingatan atas Raja Sangihe Penantang VOC, kita merawat akal sehat maritim Indonesia—bahwa laut bukan halaman belakang, melainkan muka rumah yang harus dijaga bersama.
Last modified: Oktober 23, 2025